Sorong, 17 Februari 2024, Taman Wisata Alam Sorong mendapat kunjungan edukasi (School Visit) dari Paud Cahaya Islam dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch II. Rombongan […]
Serunya Kunjungan Edukasi Sebagai Upaya Bina Cinta Alam di Taman Wisata Alam Sorong
Sorong, 17 Februari 2024, Taman Wisata Alam Sorong mendapat kunjungan edukasi (School Visit) dari Paud Cahaya Islam dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch II. Rombongan berjumlah sekitar 200 orang dengan […]
Read morePengendali Ekosistem Hutan Balai Besar KSDA Papua Barat berhasil mendapatkan penghargaan Elodie Sandford Explorer 2023 dari Scientific Exploration Society
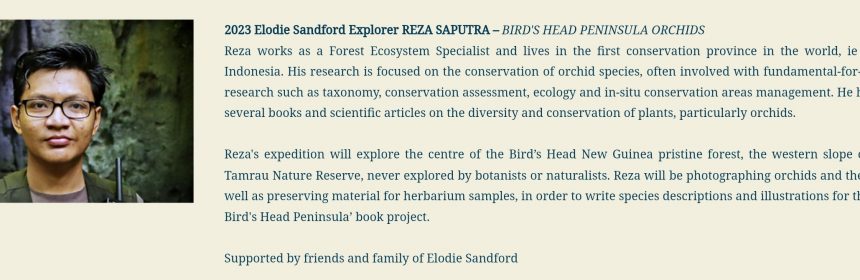
Pada penghujung tahun 2023, terdapat prestasi yang membanggakan dari Balai Besar KSDA Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama dari Balai Besar KSDA Papua […]
Read moreKeindahan Tarian Cendrawasih Merah di Kampung Warkesi
Selain memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa, Raja Ampat juga memiliki hutan yang menjadi rumah bagi berbagai satwa endemik. Menurut data dari pemerintah, ada 258 spesies burung dan […]
Read morePeningkatan Kapasitas Pemandu Wisata Alam Di TWA Sorong
Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi pemandu wisata, Balai Besar KSDA Papua Barat berkolaborasi dengan Fauna & Flora International Programme Tanah Papua, melaksanakan pelatihan bagi pemandu wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama […]
Read morePelatihan Penanganan Satwa
Tanah Papua memiliki potensi keanekaragaman hayati yang begitu melimpah. Setidaknya tercatat terdapat sebanyak 339 jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi undang-undang (37,5%) berada di Tanah Papua dari total […]
Read moreMikroorganisme di Ekosistem Hutan: Kunci Kehidupan

Artikel ini akan memberikan pandangan yang jelas kepada pembaca yang masih awam tentang konservasi hutan, manfaat mikroorganisme, dan keajaiban yang diciptakan melalui keberadaannya. . Ekosistem hutan adalah salah satu keajaiban […]
Read moreMengungkap Misteri Kuskus Totol Waigeo: Spilocuscus Papuensis

Waigeo, sebuah pulau indah di Provinsi Papua Barat, Indonesia, terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Selain terumbu karang yang menakjubkan, hutan hujan yang megah, dan satwa liar yang eksotis, […]
Read morePeranan Penting Burung dalam Ekosistem Hutan Indonesia

Hutan Indonesia adalah salah satu aset alam yang paling berharga di dunia, dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan ekosistem yang unik. Burung adalah bagian integral dari ekosistem hutan ini dan […]
Read moreKeajaiban Polinator: Penjaga Ekosistem yang sering tidak dianggap

Polinator adalah makhluk kecil yang sering terlupakan, tetapi peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan mengapa polinator sangat berharga dan bagaimana kita dapat […]
Read morePeranan Ular dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Hutan

Hutan Indonesia adalah salah satu aset alam terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di dalam keanekaragaman ini, ular-ular Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan […]
Read more









